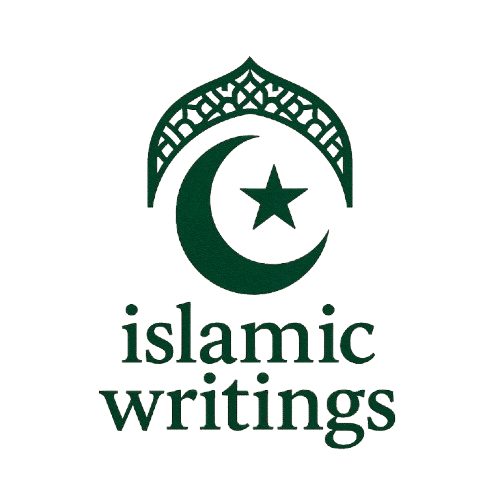Banyak yang mengira bahwa sistem perpajakan merupakan produk zaman modern. Namun, dalam sejarah Islam, sistem serupa telah dikenal sejak masa Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. Sebagai kepala negara dan pemerintahan, Rasulullah menerapkan sejumlah bentuk pungutan yang menjadi sumber pendapatan negara.
Dalam berbagai literatur sejarah Islam, disebutkan bahwa terdapat enam sumber pendapatan negara di masa Rasulullah, yaitu:
-
Harta rampasan perang (ghanimah)
-
Harta musuh yang diperoleh tanpa peperangan (fai)
-
Zakat
-
Pajak tanah (kharraj)
-
Pajak kepala (jizyah)
-
Hadiah dari negara sahabat
Dari keenam sumber tersebut, empat di antaranya (selain ghanimah dan fai) menjadi sumber pemasukan tahunan negara.
Zakat, sebagai kewajiban umat Islam, hanya dibebankan kepada kaum Muslim. Namun, umat Islam juga dikenai pajak dalam konteks tertentu, terutama untuk mendukung kebutuhan negara. Sementara itu, penduduk non-Muslim dikenai pajak berupa jizyah dan kharraj sebagai bentuk kontribusi terhadap negara yang menjamin keamanan dan hak-hak mereka.
Pengumpulan Zakat dan Pajak di Masa Nabi SAW
Seiring meluasnya wilayah kekuasaan Islam, jumlah pembayar zakat (muzakki) pun meningkat. Untuk itu, sekitar tahun ke-9 Hijriyah, Rasulullah mengangkat para petugas zakat (amil) guna menghimpun zakat dari berbagai suku. Para amil ini tidak hanya mengumpulkan zakat, tetapi juga bertugas memungut jizyah dan kharraj. Biasanya, kepala suku diangkat sebagai amil sementara untuk komunitasnya masing-masing.
Sistem ini kemudian dilanjutkan oleh para khalifah setelah Rasulullah. Pada masa Umar bin Khattab, sistem pajak mulai ditertibkan dan disusun secara sistematis, khususnya dalam hal pengelolaan kharraj. Namun, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, sistem tersebut mengalami kemunduran karena adanya perlakuan istimewa terhadap kerabatnya terkait tanah. Meski begitu, pada masa inilah cikal bakal departemen perpajakan mulai dibentuk. Di era Ali bin Abi Thalib, reformasi dilakukan dengan mencopot para gubernur lama dan mengembalikan hasil tanah kepada negara serta menerapkan kembali distribusi pajak tahunan seperti era Umar.
Pandangan Ulama tentang Pajak
Dalam khazanah fiqih Islam, pajak (adh-dhara’ib) menjadi bahan perdebatan. Empat mazhab utama Islam membolehkan pajak yang adil sebagai biaya untuk kepentingan umum. Namun, sebagian ulama menolaknya jika dianggap menyerupai al-maks (pungutan liar).
Mazhab Maliki menyebut pajak sebagai wazha-if atau kharraj, sedangkan mazhab Hanafi menyebutnya nawa’ib (bentuk jamak dari naaibah), yakni bentuk pengganti kewajiban dari pihak penguasa. Pengikut mazhab Hanbali menyebutnya kulfah sultaniyah, yaitu beban harta yang diwajibkan oleh penguasa.
Pajak yang disebut “adil” adalah pajak yang memiliki manfaat nyata, bersumber dari kekayaan yang layak, dan digunakan untuk kepentingan rakyat seperti pembangunan, pendidikan, kesehatan, serta keamanan.
Imam Adz-Dzahabi dalam Al-Kabaair menyebutkan:
“Pemungut pajak adalah bagian dari kezaliman jika memungut apa yang tidak seharusnya dan memberikannya kepada yang tidak berhak.”
Karena itu, mayoritas ulama klasik dan kontemporer sepakat bahwa pajak diperbolehkan selama adil dan tidak membebani rakyat secara berlebihan. Jika pajak menindas atau merugikan rakyat, maka hukumnya menjadi haram.
Pajak di Era Modern: Antara Kebutuhan dan Keadilan
Syekh Abdullah Al-Faqih dalam fatwa di Fatawa Asy Syabakah Al-Islamiyah menyatakan bahwa pajak yang digunakan untuk kepentingan umum diperbolehkan. Namun, jika kebutuhan negara sudah tercukupi dari sumber lain, maka pajak tidak diperlukan.
Ustaz Farid Nu’man, dai lulusan Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa kondisi setiap negara berbeda. Di Indonesia, misalnya, sekitar 70% belanja negara ditopang oleh pajak. Melarang pajak secara mutlak, menurutnya, bisa menyebabkan kekacauan fiskal.
“Kalau kekayaan negeri ini dikelola dengan baik, sebenarnya Indonesia bisa berjalan tanpa pajak seperti Arab Saudi,” ujarnya.
Dengan demikian, sistem pajak dalam Islam memiliki akar historis yang kuat dan telah dijalankan secara sistematis sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada prinsipnya, pajak yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat luas diperbolehkan, asalkan tidak memberatkan dan disalurkan dengan transparan serta bertanggung jawab.